KIMIA DAN LINGKUNGAN: Rekam Jejak CFC dan Ozon
Hai semua. Salah satu masalah pencemaran kimia dan lingkungan yang sangat menonjol adalah adanya penipisan lapisan ozon.
Penipisan ozon pertama kali ditemukan di stratosfer sekitar sepuluh kilometer di atas Antartika oleh ilmuwan dari British Antarctic Survey (Inggris), Joseph Charles Farman.

J.C. Farman atau Joe Farman mempublikasikan penemuan lubang ozon bersama dua rekannya, Brian Gardiner dan Jon Shanklin dalam jurnal Nature pada 16 Mei 1985.
Fakta menakjubkannya, pada 25 Maret 2020, sebuah makalah ilmiah karya salah seorang peneliti dari University of Colorado, Antara Banerjee, yang dipublikasikan dalam jurnal Nature menyebutkan bahwa lubang ozon di atas Antartika mengalami pemulihan (mulai menutup).
Antara Banerjee mengaku menggunakan data dari pengamatan satelit dan simulasi iklim untuk mendeteksi pemulihan ozon. Banerjee dkk. juga memodelkan perubahan pola angin terkait dengan pemulihan lapisan ozon.
Dengan metode itu, Banerjee menyampaikan pemulihan ozon sebagian besar berkat Protokol Montreal yang disepakati secara internasional pada tahun 1987, yang melarang produksi zat kimia perusak ozon, seperti CFC.
Apa itu CFC? Mengapa CFC dapat merusak lapisan ozon?
(baca juga PENJELASAN OZON DAN PENGARUHNYA TERHADAP LINGKUNGAN)
Yuk kita bahas!!
CFC adalah chlorofluorocarbon, yaitu senyawa organik alifatik yang tersusun atas unsur klorin, fluorin, dan karbon. Sintesis CFC pertama kali dilakukan oleh ahli kimia Belgia, Frédéric Swarts (1866-1940), meliputi proses berikut:

Kemudian untuk meminimalisir biaya pembuatannya, pembuatan CFC meliputi:

Pada pertemuan American Chemical Society (ACS) pada tahun 1930, Insinyur kimia Amerika Serikat dari General Motors, Thomas Midgley Jr., mengumumkan sintesis CFC dari proses Swarts tersebut. Midgley mendemonstrasikan sifat fisik CFC dengan menghirup uap CFC dan menghembuskannya ke api lilin yang padam. Hasilnya menunjukkan bahwa CFC tidak beracun, dan tidak mudah terbakar.
Di tahun yang sama, General Motors dan Du Pont de Nemours, Inc., Perusahaan Amerika Serikat, membentuk Kinetic Chemical Company untuk memproduksi CFC. Du Pont mendaftarkan CFC ini dengan merek dagang yang dikenal dengan nama Freon.
Tentang CFC
Dua CFC yang umum adalah CFC-11 (Trichloromonofluoromethane) dan CFC-12 (Dichlorodifluoromethane).

Senyawa CFC secara luas dipakai untuk pendingin ruangan (air conditioner/AC), sebagai refrigeran (media pendingin) pada kulkas menggantikan gas beracun, amonia (NH3), metil klorida (CH3Cl), dan sulfur dioksida (SO2) yang digunakan sampai awal 1930-an. Selain itu, CFC juga banyak digunakan sebagai blowing agent dalam proses pembuatan foam (busa), sebagai cairan pembersih (solvent), dan bahan dorong dalam aerosol (penyemprot/spray).
Bahaya penggunaan CFC bagi lingkungan baru diketahui tahun 1974 dengan hipotesis penipisan lapisan ozon oleh ilmuwan dari Universitas California dan Universitas Michigan di Amerika Serikat, Sherwood Rowland dan Mario Molina.
Ozon atau trioksigen adalah molekul anorganik dengan rumus molekul O3.
Ozon dapat ditemukan di dua lapisan atmosfer, di mana 10% dari total ozon ditemukan di troposfer, dan 90% ozon ditemukan di stratosfer. Ozon di stratosfer disebut lapisan ozon yang tersusun oleh molekul-molekul ozon.
 Sumber:sekilasatmosfer.wordpress.com
Sumber:sekilasatmosfer.wordpress.com
Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon (O3) terjadi secara alami di stratosfer. Hal tersebut dikarenakan ikatan antara atom oksigen dalam molekul ozon agak lemah dibandingkan dengan molekul oksigen (O2), sehingga salah satu dari ketiga atom oksigennya mudah lepas dan bereaksi dengan molekul yang lain, misalnya CFC.
Nah, bagaimana proses penipisan lapisan ozon oleh CFC?
Coba perhatikan animasi berikut.

CFC termasuk senyawa BPO (Bahan Perusak Ozon) yang stabil sehingga banyak digunakan karena dianggap aman. Namun, kestabilan CFC tersebut menyebabkan CFC sulit terurai.
Nah, ketika AC atau kulkas yang mengandung CFC mengalami kebocoran, maka CFC akan bergerak naik bebas dengan perlahan ke dalam stratosfer. Oh ya, karena kestabilannya, CFC tidak terurai pada lapisan atmosfer paling bawah, yaitu troposfer.
Di lapisan stratosfer, CFC akan melepaskan khlorin karena terkena radiasi sinar ultraviolet (UV-B) yang berasal dari matahari.

Atom klor yang merupakan radikal bebas bereaksi dengan molekul ozon dan memecahnya menjadi klorin monoksida dan molekul oksigen. Ozon menjadi hancur.

Molekul klorin monoksida masih reaktif dan bereaksi dengan atom oksigen yang seharusnya dapat membentuk ozon. (Ingat: Ozon terbentuk dan terurai secara alami).

Atom klor yang terbebas akan kembali merusak ozon. Reaksi-reaksi di atas terjadi berulang-ulang dengan akibat rusaknya atau semakin menipisnya lapisan ozon.
Setiap satu molekul CFC mampu menghancurkan hingga 100.000 molekul ozon, loh.
Coba kalian bayangkan masalah kimia dan lingkungan ini, jika lapisan ozon rusak maka siapa yang akan melindungi bumi dari bahaya sinar ultraviolet?
Nah, menyadari pentingnya melestarikan lapisan ozon, Publik Internasional pun berusaha mencegah penipisan lapisan ozon bumi. Dimulai sejak Konvensi Wina 1985, dan ditindaklanjuti dengan Protokol Montreal pada September 1987. Protokol Montreal menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh para pihak untuk membatasi produksi dan konsumsi BPO yang diawasi yaitu CFC dan Halon pada bahan pemadam kebakaran.
Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud BPO (Bahan Perusak Ozon) bukan hanya CFC saja, melainkan senyawa kimia yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, klorin dan/atau bromin, seperti Halon, Hidrochlorofluorocarbon (HCFC), Metil bromida pada pestisida, Karbon tetraklorida (CTC), dan Metil Chloroform (TCA).
Peran Pemerintah
Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, sudah berupaya dan berkomitmen untuk mengurangi produksi dan konsumsi BPO. Indonesia meratifikasi Protokol Motreal dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992.
Pada tahun 1988, Indonesia melarang impor BPO jenis Halon, Methyl Chloroform (TCA), hingga Carbon Tetrachloride (CTC). Lalu pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007, Indonesia melarang impor Methyl bromide, dan hanya diperbolehkan untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan. Berikutnya melarang penggunaan CFC, R-500, R-502, dan Halon pada produksi mesin pengatur suhu udara (AC).
Pada tahun 2009, Indonesia melarang produksi obat jadi menggunakan CFC hingga penghentian pendaftaran Metered Dose Inhaler yang menggunakan CFC oleh BPOM. Selanjutnya pada 2015, melarang impor barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan refrigerant HCFC-22 dalam kondisi terisi maupun kosong. Terakhir, refrigerant HCFC-22 masih diperbolehkan digunakan untuk kebutuhan perawatan mesin AC dan refrigerasi sampai dengan 2030.
Wah, satu langkah tepat telah ditempuh untuk keselamatan kita dan Bumi kita, ya teman!
Oleh karenanya, marilah kita ikut berpartisipasi dalam melestarikan Sang Pelindung, Ozon. Salah satunya dengan menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih produk-produk yang tidak mengandung BPO/ozon-friendly. Selain itu, dengan kita mengurangi penggunaan AC. menghindari memakai parfum semprot dengan aerosol, serta mulai memakai produk pembersih alami juga dapat membantu meminimalisir proses penipisan lapisan ozon. Many ways to be more ozon-friendly. Lets take actions for our future planet!!
Sekian ya, semoga artikel kimia dan lingkungan ini bermanfaat bagi kalian, terimakasih.
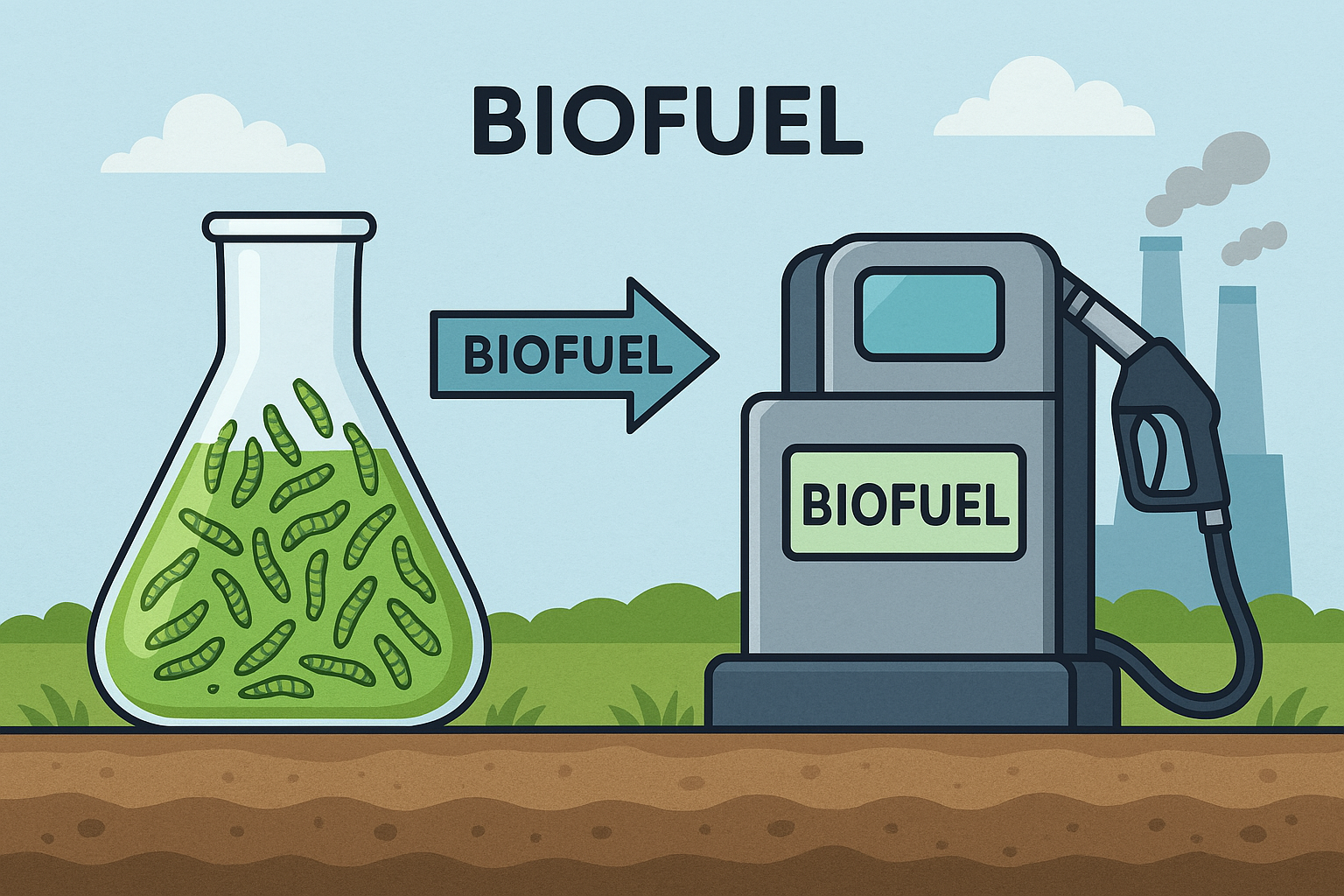


Post Comment